Setiap kali menemukan buku bacaan yang
meninggalkan kesan mendalam, aku selalu terpesona karena buku-buku itu
sejatinya adalah jalinan huruf yang menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat
menjadi paragraf dan terbentuklah sebuah cerita yang utuh. How could 25 alphabets transform into million
stories? Ini baru ngomongin cerita yang ditulis menggunakan alfabet, belum lagi
cerita-cerita yang disampaikan menggunakan aksara lain.
It got me goosebump,
always. Apalagi kalau isi bukunya ternyata relate banget dengan diri sendiri,
berasa pikiran kita sedang terwakilkan oleh sebuah buku (trust me, it happens
to every reader) (if you're a reader and its not happening yet in your life, just keep reading new book), sampe bikin momen KOK BISA PIKIRAN KITA SAMA??!
Tahun 2022 aku
mengeksplorasi banyak penulis baru yang karyanya belum pernah aku baca, di
antara penulis-penulis tersebut, yang paling meninggalkan kesan
I-found-my-new-favorite-author adalah Mitch Albom ketika membaca bukunya
yang berjudul Orang Berikut yang Kau Jumpai di Surga a.k.a The Next Person You
Meet in Heaven. Ceritanya tentang seorang perempuan yang mengalami kecelakaan
saat kecil dan membuatnya cacat fisik permanen, lalu ada serangkaian peristiwa
yang dialami oleh perempuan tersebut dan dilukiskan oleh Mitch Albom dengan
kalimat we forget that our time is linked to others times. We come from one.
We return to one. That’s how a connected universe makes sense.
Kita lupa bahwa waktu
kita terikat dengan waktu orang lain. Itulah bagaimana semesta saling
terkoneksi.
Sebagai orang yang
super canggung membuka obrolan dengan stranger membuatku lebih senang
menjadi observer. I like watching people around and make a story
about how's their life by my imagination. Kadangkala sambil mikir –seperti
yang sudah diwakilkan oleh kalimatnya Mitch Albom–bahwa tidak ada kejadian yang
terjadi secara acak, bahwa kita tidak bisa memisahkan satu kehidupan dengan
kehidupan lain karena takdir manusia bersinggungan satu sama lain, berwujud
sebab-akibat yang bahkan tidak disadari oleh manusia itu sendiri. Kalau kalian
baca The Next Person You Meet in Heaven (rekomended btw) (bolelah ngantri
minjem di iPusans kalau mau baca gratis), kita bisa melihat bagaimana satu
peristiwa kecil yang sederhana memberi efek pada peristiwa besar, perasaan dan
kemauan yang dirasakan oleh manusia lalu menimbulkan aksi tertentu dapat
menimbulkan serangkaian kejadian yang tidak terduga dan semua itu diramu oleh
Mitch Albom dengan mengombinasikan 25 huruf alfabet yang seakan-akan ingin
menunjukkan pada pembacanya tentang every little thing that you did could
give an impact to others life.
Life is full of
surprise, isn’t it?
Memang rata-rata
manusia hanya bisa mengingat paling banyak 2000 nama orang, mengenal 500 orang,
berteman dan menjaga hubungan sosial dengan kisaran 150 orang, bahkan hanya mampu
maintain closer friendship sebatas 5~15 orang, itu pun gak semua orang punya
close friend #yaha, tapi setiap orang pasti pernah bersinggungan dengan orang
asing. Apakah interaksi kita dengan para orang asing ternyata menimbulkan
peristiwa lain bukanlah sesuatu yang selalu bisa kita ketahui, namun bukan berarti
interaksinya tidak bisa diceritakan.
Tulisan ini berisi
potongan ingatan yang kumiliki hasil dari bersinggungan dengan orang asing
–baik menimbulkan interaksi secara langsung atau tidak– ketika aku berstatus
sebagai penjelajah mandiri dan mengunjungi beberapa kota di Indonesia pada dua
quarter pertama tahun 2022.

Bisa menginjakkan kaki
di Bandar Udara Kualanamu merupakan hal yang tidak pernah kupikir akan kucapai tahun ini. Pertama kali mendengar nama Kualanamu dengan fasilitas kereta
bandaranya–hal yang jarang pada saat itu karena soetta aja belum punya– saat
masih SMA, aku udah punya keinginan untuk melihat Kualanamu. Punya keinginan
tapi nggak tau kapan terealisasi karena Sumut itu jauh dan gak ada urusan juga
buat ke Sumut. Meski punya teman yang tinggal di Sumut tapi nggak pernah muncul
ide 'oke, aku mau ke Sumut dari Malut untuk mengunjungi rumah Ula.' AKU NGGAK SEgILA ITU. Well, bukan gila, tapi
emang gak punya duit aja, sih, WKWK. Long story short, ternyata aku bisa menginjakkan kaki di Sumut untuk… ketemu Ula HAHAHAHA. Padahal rencananya mau ke Sumatra Utara naik Bus *sobat hemat ceunah* namun berkat rizki Allah Swt. yang memang tidak
bisa diprediksi arah datangnya, aku bisa naik pesawat dari Jakarta ke Medan.
Kualanamu, I am comingg~
Berhubung lokasi Kualanamu International Airport terletak di kabupaten Deli Serdang sedangkan rumah Ula di kota Medan, dari bandara aku perlu melanjutkan
perjalanan lintas kota menggunakan Bus Gagak Hitam (yang ternyata warna kuning) menuju kota
Medan. Sembari memegang segelas Americano dari Kopi Kenangan, aku naik Bus dan mendapat
bangku di paling depan, serong kananku ada pak sopir dan sebelah kiriku ada
seorang mas-mas yang juga duduk. Sudah lupa bagaimana mulanya, sepertinya hanya
basa-basi Mas dari mana? Mbak dari mana? Dan ternyata kami tadi satu penerbangan
rute Jakarta – Kualanmu menggunakan Super Air Jet, pertanyaan basa basi berlanjut dengan Mas mau kemana?
Mbak mau kemana?
"Saya mau ke Aceh tapi
kehabisan tiket pesawat jadi lewat Medan, nanti baru lanjut Bus ke Aceh."
Kita sebut saja mas
ini dengan nama mas Aceh.
Perjalanan Bandara – kota Medan memakan waktu
sekitar satu jam jadi percakapan basa-basiku dengan mas Aceh tetap berlanjut mengalir apa adanya, aku senang-senang saja diajak ngobrol. Selalu menyenangkan
bisa mengobrol dengan orang asing di perjalanan.
"Mas namanya siapa?"
Dia menyebut nama
panggilannya lantas bertanya, "bisa nebak tidak nama lengkap saya?"
Hmm, apa karena dia tau latar belakang pendidikanku lantas berpikir aku adalah cenayang? ahli menebak nebak?
Karena aku menggeleng, mas Aceh menyebut nama lengkapnya yang terdengar berpola (seperti susi susanti, bambang herlambang, cahyo kuncoro, semacam itu lah) dan bertanya balik, "Mbak nama lengkapnya
siapa?"
Kusebut nama
lengkapku.
"Namanya adem, hehe."
EH?
Adem? Perasaan nama
gue kaga ada unsur AC atau kipas angin, bukan pula semilir dan sepoi. Adem dari
mana, dah?
"Boleh minta nomor
hapenya?" tanya mas Aceh dengan nada sopan.
Lantas aku memberitahu
nomorku yang langsung ditelpon oleh mas Aceh, supaya aku bisa menyimpan
nomornya juga. Sebuah tindakan impulsif yang tidak bisa kuhindari karena belum
pernah ada yang minta nomor kontak dan aku tidak tahu bagaimana caranya menolak tanpa merasa awkward.
Begitu sampai di rumah Ula, baru aja naruh barang dan selfie (untuk dikirim ke grup kontrakan) (harus pamer!) (wkwk), aku melihat sudah ada pesan masuk dari mas Aceh.
Hmm.
"Blokir aja!" kata Ula begitu kuceritakan tentang mas Aceh yang menghubungiku, "Kayaknya kamu
nggak punya kewaspadaan diri, deh, Wa." Lanjutnya saat tahu mas Aceh menemukan akun Instagramku dan mengirim permintaan pertemanan di facebook padahal aku tidak membagikan akun sosmedku.
Sarannya
langsung kuturuti karena aku sendiri merasa aneh, meski ada perasaan bersalah
juga karena aku belum pernah memblokir orang yang perilakunya sopan –yah
setidaknya itu yang kulihat dalam perjalanan puluhan menit di atas bus–
Kalau kata Amba di
novel Amba, perjalanan melatih diri untuk tetap
menjaga jarak seraya berbagi begitu banyak. Barangkali aku udah kelamaan tidak melakukan
perjalanan seorang diri, sekalinya perjalanan langsung kelepasan. Mengenalkan
diri dengan nama depan, memberitahu nama lengkap, bahkan membagikan nomor
pribadi.
Yha.
Sebenarnya
ketika melakukan perjalanan, aku tidak pernah mengenalkan diriku dengan nama
depan. Selain nama aku sedikit ribet di pelafalan (Sofa? Sofwa? Sohwa? Sobua?
Sopa? Sofi?), menjaga identitas pribadi itu perlu makanya aku mengandalkan dua
suku kata terakhir dari nama lengkapku: Nisa. Nisa lebih mudah dilafalkan dan
sudah menjadi nama yang umum dijumpai.
Berkaca dari
kesalahan saat bertemu mas Aceh, ketika aku melanjutkan perjalanan dari Medan
menuju Payakumbuh, aku bertemu seorang ibu yang duduknya di sebelahku. Dengan
semangat mengobrol-sama-orang-asing, aku menyapa ibu itu dengan pertanyaan basa
basi ibu mau kemana? (ternyata mau ke daerah di ujung Sumut) lalu ibunya
bercerita tentang semua anaknya yang sudah menikah, dia dan suaminya
sehari-hari mengurus kebun, sesekali pergi ke sanak saudara yang berbeda
provinsi, kadangkala pergi ke Medan.
"Nama kamu ada
marganya, nggak?"
"Nggak, bu,
saya nggak pake marga."
Lantas ibunya
merocos tentang kabupaten X didominasi marga Z, betapa pentingnya marga dsb
dsb, ternyata Sumatra Utara kental dengan banyak marga dan tiap marga memili kasta.
Perjalanan
darat membuatku sadar betapa luasnya wilayah Sumatra Utara. Berangkat pagi dari
Medan, lepas Isya masih berada di Sumatra Utara, belum pindah provinsi. Sebagai
penduduk yang berasal dari kabupaten kepulauan, tentu kennot relate,
wkwkw.
Saat di Medan,
panggilan mas berubah jadi abang, mbak berubah jadi kakak. Begitupun saat di
Payakumbuh, logat abang-kakak masih kental berasa sedang berada di wilayah baru
(ya emang benar) (pertamakali menjelajah Sumatra selain Lampung). Nah, saat aku sudah tiba di
Lampung, panggilan abang-kakak seketika berubah jadi mas-mbak dengan percakapan-percakapan
menggunakan bahasa Jawa yang berlogat medhok.
Heh? Aku masih di
Sumatra kan, ini? Belum nyampe Jawa, lho.
Memang benar, Lampung adalah Jawa yang nyasar ke Sumatra.
Setelah Lampung, kota tujuanku selanjutnya adalah Jogja tapi aku harus transit ke Depok dulu untuk menemani kak Muna menghadiri undangan pernikahan seorang kenalan di Bandung.
Keuntungan menjadi lajang yang bebas adalah kamu bisa fleksibel dengan itinerary perjalananmu~
Karena udah menaiki dua
bus dengan dua rute: Medan – Payakumbuh, Payakumbuh – Lampung. Aku memilih moda
transportasi lain untuk menuju Depok, pilihanku jatuh pada travel karena
dijemput di lokasi dan diantar di lokasi tujuan jadi bisa duduk nyaman. Begitu pikirku.
Malang tak dapat
ditolak, karena melakukan perjalanan yang bertepatan dengan musim mudik membuat travel yang hendak kunaiki masih
tertahan di pelabuhan penyeberangan. Jadwal travelku jam 8 malam, jam 10 malam mobilnya masih di atas laut sedang menyeberangi selat Sunda menuju
Bakauheni. Long story short yang sebenernya ada drama tersendiri karena aku membatalkan
pesanan travel dan nggak punya tempat menginap di Bandar Lampung, keesokan paginya
aku berhasil mendapatkan travel lain dengan harga sedikit lebih mahal. Aku orang
terakhir yang dijemput dan di dalam travel ada seorang mbak dan seorang mas
yang sedang asyik mengobrol, tidak niat menguping tapi logis aja kalau sedang
di dalam mobil yang sama lantas bercakap-cakap, pasti akan terdengar oleh
penumpang lain, bukan?
Sopir travel membagikan makan siang ketika mobil kami sedang mengantri untuk masuk ke kapal di pelabuhan Bakauheni, “tadi gue request ke
sopir minta tambah telur, cuma bayar goceng, murah banget.” Komentar mbak
kuncir kuda saat mendapat nasi makan siang.
“lu tadi bilang kerja
di bank mana? Temen gue ada yang di situ juga, kali aja kenal.”
Obrolan mereka berdua
didominasi oleh mbak kuncir kuda, potret wanita ibu kota independen nan open
minded amat kental dari dirinya, sedangkan mas kacamata menimpali obrolan dengan kalem. Sesaat sebelum mobil terparkir rapi di dalam kapal, tetiba mbak kuncir kuda berkata ke mas Kacamata,
“Gue gak percaya
Tuhan.”
Ketika hendak turun
dari mobil, ku lirik tangan mbak kuncir kuda yang sedang memegang sebuah buku.
Muhammad-nya Karen
Armstrong.
Selain mbak kuncir
kuda dan mas kacamata yang posisinya sejajar dengan kursiku di baris kedua, di bagian belakang
mobil duduk seorang ibu dengan anak laki-lakinya. Sembari menunggu kapal sandar dengan sempurna di pelabuhan Merak, aku sempat mengobrol dengan si ibu yang sedang mengisap sebatang rokok.
“Anak saya… indigo.” ujar si ibu menunjuk laki-laki yang berdiri tak jauh dari dirinya.
“Oh, iyakah?”
“iya, sstttt tapi diam
diam saja.”
Aku mengangguk.
“Dia bisa meramal masa depan, tapi saya bilang ke dia kalau jangan cerita-cerita ke orang lain."
Anak laki-laki si ibu –yang ternyata sebaya denganku- terlihat seperti
seseorang dengan spektrum autism, tidak fokus, tidak bisa diajak ngobrol lama,
menggumam sendiri, barangkali usia mentalnya masih belasan atau bahkan di bawah
10 tahun. Indigo? Ndak, aku ndak percaya.
Begitu sampai Jogja, aku menginap di rumah Putri beberapa hari. Dalam rentang waktu menginap tersebut, aku sempat pergi ke beberapa tempat, salah satunya puncak Bibis.
Ketika kami sedang duduk di puncak Bibis menunggu pesanan makanan kami datang, tanpa sengaja telingaku mendengar suara perempuan yang
sedang bercerita dengan menggebu-gebu, aku mencari-cari sumber suara dan sekitar 7 meter dari tempat kami, mataku menangkap dua sosok orang perempuan yang duduk berhadapan. Ternyata memang ada yang lagi sesicurhat.
“udah aku bilangin
kalau xxxxx.”
“menurutku, yang
salah zzzzzzzzzzzz.”
Mulanya kupikir
curhatan seorang wanita yang sedang menceritakan pacarnya, makin didenger kok
ada kata-kata ‘mertua’ ‘rumah’ 'keluarga' 'ipar.'
Pertengkaran suami-istri?
Ada rasa gatel kepo pengen dengerin curhatannya (yang bisa didengar jelas karena suara mbaknya keras) tapi atas asas menghormati, aku berusaha lebih fokus dengerin live music yang sedang memainkan lagu lokal (meski suara mbaknya tetap sayup-sayup terdengar). Ketika live music-nya sempat
terhenti, mau nggak mau obrolan dua perempuan itu masuk ke telingaku, aku menahan diri untuk nggak menoleh.
Pesanan kami datang, kami mengobrol, kami makan, kami salat magrib, bahkan setelah berbagai kegiatan yang aku dan Putri lakukan, curhatan mbak-mbak itu masih belum berakhir. Perempuan kalau ngobrol bisa lama banget, ye.
#NggakNgaca
Satu hal yang aku
pelajari: jika hendak menceritakan sebuah masalah, ruang tertutup dan suara yang pelan adalah dua hal
yang perlu diperhatikan.
“Mbak mau kemana?”
“Ternate, mas.”
“Saya kemarin baru aja
dari Papua.”
“Wah, jauhnyaa,
ngapain ke Papua?”
“Jalan-jalan, saya
tiga bulan di Papua.”
Pagi hari dalam
perjalanan menuju bandara Juanda, bertemu sopir Grab yang baru saja keliling tanah
Papua, cerita kalau sempat sakit dan diobati dengan obat lokal, mencoba makanan
yang enak-enak, medan tujuan yang tidak selalu mulus, keindahan alamnya yang
menakjubkan.
“Kalau di Ternate ada
apa, mbak?”
“Err… apa, ya. Saya
kan di Maluku Utara, kalau makanan, mirip-mirip kayak Papua. Seafood, papeda,
gitugitu lah.” #BukanDutaPariwisata
“Dua tahun lalu saya
tiga bulan di Kalimantan, tahun ini rencananya mau ke Labuan Bajo.”
Aku yang empat bulan
terakhir menjelajah langsung diingatkan, “Janganlah jumawa~ nyoh si Mas lebih
keren dari kamu.”
Ternyata begitu tiba
di Bandara Internasional Juanda, aku kepagian karena konter check-in untuk
penerbanganku belum dibuka. Ketika lagi nyari tempat duduk, aku lihat ada mesin
self-check in, akhirnya aku nyetak boarding pass dulu lalu tetap duduk sembari
nunggu konter check-in dibuka karena aku perlu naruh bagasi.
“Mbak.”
Ada yang manggil.
“Bisa cetakkan tiket?”
Seorang Ibu berkerudung cokelat tua yang duduk
berjarak dua kursi di sebelah kananku bertanya sembari menyerahkan selembar kertas
ukuran HVS.
Aku mengangguk, sudah lama aku tidak melihat tiket yang di-print di kertas HVS padahal yang dibutuhkan hanya kode booking saja. Mengingatkan masa aku masih bawa-bawa kertas HVS setiap check-in saat SMP.
“Ini, bu, tiketnya.
Kalau ada bagasi masih perlu nunggu karena konternya belum buka, kalau nggak
ada bagasi bisa langsung ke ruang tunggu.”
Sekitar hampir satu
jam kemudian, konter check-in akhirnya dibuka, aku langsung mengantri untuk
naruh koper, bu Cokelat juga mengantri karena tujuan dan maskapai kami sama: Lion Air menuju Ujung Pandang.
Ibu Cokelat berdiri di depanku, begitu mendekati konter tampak ibu cokelat menyingkirkan koper cokelat cabin-size nya dari antrian.
“Loh? Kok kopernya
dipinggirin?” Batinku heran, karena koper itu satu-satunya bawaan ibu Cokelat.
“Bu, ini kopernya mau
dibawa masuk ke dalam pesawat?”
“Iya.”
“Kalau gitu nggak
perlu ngantri di sini. Ibu bisa langsung ke ruang tunggu saja.”
“Oh, begitu.”
Lantas ibu Cokelat
langsung balik badan, pergi. Aku lanjut mengantri, meski bawaanku juga koper
cabin-size tapi ogah banget geret koper ke dalam kabin.
Sampai sini aku mulai
mengira, “Jangan-jangan ibunya baru pertama kali naik pesawat? Tadi tiketnya
juga masih di-print pake kertas HVS.” Cuma karena sejak awal ibu Cokelat gaada gelagat
bareng-yuk-mbak soalnya langsung ngeloyor pas aku kasih tau counter check-in udah buka,
akhirnya aku pun tidak berinisiatif untuk mengajak sama-saya-yuk-bu.
Begitu selesai menaruh koper -setidaknya menghabiskan waktu 15 menit- aku langsung menuju waiting room... KOK IBU COKELAT MASIH DI SITU?
Beliau berdiri di dekat mesin self-check in.
"Ibu mau ke ruang tunggu?"
"Iya."
"Kalau gitu, arahnya kesini."
Kami sama-sama menuju antrian pengecekan untuk masuk ruang tunggu, dan ibu Cokelat kembali meninggalkan aku wkwkw. Sampai sini aku merasa bu Cokelat kebingungan tapi juga gak ada inisiatif untuk barengan.
Ruang tunggu Juanda, kan,
luas banget. Ada banyak Gate. Begitu selesai melewati area pengecekan arahnya bisa
belok kiri atau belok kanan tergantung penerbangannya di gate berapa. Lagi-lagi aku melihat bu Cokelat hanya berdiri di persimpangan. Kali ini aku nggak menyapa karena berniat untuk mampir beli kopi tapi aku memastikan beliau melihatku karena beliau tau kami di maskapai yang sama. Aku berjalan dengan pelan menuju gate penerbanganku sembari mencari gerai minuman yang menjual kopi, bu Cokelat
berada tak jauh di belakangku, setidaknya beliau bisa liat aku sekiranya butuh
arahan kudu jalan kemana.
Mataku menangkap The Coffee Bean, namun aku urung mampir karena cukup ramai, "nanti aja deh, beli kopinya di Makassar aja," aku langsung menuju gate-ku dan tanpa direncana duduk tepat di samping ibu Cokelat.
Ternyata ibu Cokelat
mau ke Mamuju tapi penerbangannya sampai Makassar aja. Dari Makassar ke Mamuju
lewat jalur darat, baru pertamakali ke Mamuju (bisa diasumsikan pertamakali
naik pesawat(?)) cuma aku nggak nanya-nanya lagi karena ibu Cokelat tidak
menunjukkan minat mengobrol.
Yaudah.
Apakah mas Aceh berhasil sampai Aceh?
Apakah ibu-ibu di bus tetap mengurus kebun?
Apakah mbak kuncir kuda dan mas kacamata masih menjalin komunikasi?
Apakah anak indigo kabarnya sehat?
Apakah mas sopir Grab melakukan perjalanan ke Labuan Bajo sesuai rencana?
Apakah ibu Cokelat sampai Mamuju dengan selamat?
Pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja terjawab jika aku memiliki hubungan dengan mereka, namun ini adalah ingatan tentang orang Asing, sehingga pertanyaan yang tampak sederhana pun jawabannya adalah misteri.
Aku tidak tahu, dan tidak akan pernah tahu.


%20_%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20-%20%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%AA.jpg)













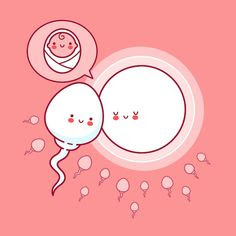









.jpeg)

